
Oleh:
Gunoto Saparie
Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah
Tidak mudah menyatukan dua orang yang terlalu dekat. Seperti dua kutub magnet yang sama, mereka justru saling tolak ketika bersentuhan. Apalagi jika keduanya merasa telah lama berdiri pada pijakan yang benar.
Itulah yang, barangkali, telah lama terjadi antara Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Dua rumah besar umat Islam Indonesia yang kadang seolah terpisah oleh pagar-pagar kecil, yang tak tampak tetapi terasa.
Mereka tidak bertengkar. Tidak sedang memusuhi satu sama lain. Namun, dalam banyak hal, juga tidak sepenuhnya saling memahami.
NU, dengan semesta pesantrennya, kitab-kitab kuning yang menguning, zikir, tahlil, dan hormat yang tak habis-habis kepada para wali dan kiai. Muhammadiyah, dengan sekolah-sekolahnya yang teratur, khutbah Jumat yang ringkas, khutbah Id yang sistematis, dan semangat purifikasi yang tak pernah lelah. Yang satu mengajak melihat sejarah sebagai warisan, yang lain mengajak melihat masa depan sebagai pembebasan.
Tetapi kita lupa, bahwa keduanya sebenarnya sedang berjalan ke arah yang sama: mencerdaskan umat, menegakkan akhlak, mengangkat martabat bangsa melalui ajaran Islam. Yang satu memilih jalan berliku dan kadang mistis. Yang satu memilih jalan lurus dan terang, meski kadang terlampau keras. Tetapi bukankah dua jalan itu bisa bertemu di satu titik, di simpang yang sama, di cita-cita yang serupa?
Upaya menyatukan NU dan Muhammadiyah, tentu bukan dalam arti meleburkan. Sebab justru keberagaman itulah yang menjadi kekayaan. Namun, menyatukan dalam semangat, dalam kegelisahan yang sama tentang arah negeri ini, dalam kekhawatiran yang sama tentang kekerasan yang mengatasnamakan agama, dalam harapan yang sama tentang Islam yang ramah, bukan marah.
Tanda-tanda itu pernah tampak. Dalam perjumpaan kultural para tokoh, dalam senyum Gus Dur dan ceramah-ceramah intelektual Buya Syafii Maarif. Dalam kerja-kerja kemanusiaan yang sama-sama mereka lakukan di Lombok dan Palu. Dalam diskusi-diskusi panjang, diam-diam, yang tak pernah masuk headline berita, tetapi bergaung pelan di pesantren dan universitas.
Yang menjadi soal barangkali bukan perbedaan fikih atau cara beribadah. Tetapi siapa yang bersedia lebih dahulu membuka diri, menyapa lebih dulu, mendengar lebih lama. Sebab seperti dua sahabat lama yang telah lama duduk saling membelakangi, mungkin yang dibutuhkan hanya sedikit keberanian untuk menoleh dan berkata, “Mari kita bicara.”
Kita tahu, bahwa setiap kali Ramadan menjelang, kita kerap kembali pada perdebatan lama yang tidak pernah benar-benar usang. Satu organisasi memulai puasa pada hari Kamis, misalnya, yang lain pada Jumat. Satu melihat ke langit, yang lain membuka tabel hisab. Lalu media sibuk membuat peta perbedaan. Judul-judul berita seolah menyambut perbedaan itu seperti musim tahunan yang tak bisa dihindari.
Tetapi tak pernah ada demonstrasi. Tak ada amarah besar. Hanya satu pertanyaan kecil yang mampir di ruang-ruang keluarga: “Besok puasa atau belum?”
Itulah Indonesia. Sebuah negeri yang, entah bagaimana, bisa menjadikan perbedaan sebagai semacam kebiasaan. Di sanalah NU dan Muhammadiyah sering berdiri berseberangan. Tapi tidak dengan wajah marah. Tidak pula dengan kata-kata kasar. Hanya berbeda dalam waktu. Dalam cara membaca langit. Dalam tafsir atas sabda Nabi Muhammad SAW.
NU tumbuh dari bumi pesantren, dari keramaian tahlilan dan kenduri, dari ziarah ke makam para wali, dari langgam Jawa yang melembutkan suara azan. Dakwahnya dekat dengan tradisi. Ia tak buru-buru meninggalkan masa lalu, sebab masa lalu baginya adalah akar yang menyangga pohon.
Muhammadiyah lahir dari ruang kelas, dari sekolah-sekolah yang rapi dan terang, dari klinik-klinik kecil yang tumbuh menjadi rumah sakit. Dakwahnya lebih rasional, sering dianggap modern, bahkan progresif. Ia memilih mengubah masa depan dengan merombak apa yang dianggap usang.
Mereka berbeda dalam pendekatan, tetapi tidak dalam cita-cita. Sama-sama ingin umat ini tercerahkan. Sama-sama ingin Islam menjadi suluh, bukan bara.
Bedanya: NU percaya bahwa suluh itu harus dibungkus dalam sapu tangan tradisi; Muhammadiyah memilih membawanya dalam senter ilmiah. Dan itu tidak harus menjadi soal.
Dalam masyarakat, NU sering hadir sebagai penjaga akar, memelihara kearifan yang tak tertulis, menyapa rakyat kecil dengan bahasa yang tak dibuat-buat. Ia mendampingi petani, nelayan, kiai kampung, dan ibu-ibu pengajian yang tak pernah membaca kitab tafsir tetapi hafal doa selamat.
Muhammadiyah, di sisi lain, tampil sebagai pelopor perubahan, pembaru sistem, penggerak pendidikan dan kesehatan, pemelihara nalar kritis dan efisiensi. Ia merintis sekolah, membangun universitas, mengelola rumah sakit dengan standar modern.
Dua pendekatan itu tidak pernah saling meniadakan. Justru saling melengkapi. Dalam demokrasi, keduanya aktif: NU dengan gerakan kulturalnya yang lentur, Muhammadiyah dengan gerakan struktural yang kokoh. Dalam pembangunan masyarakat, keduanya hadir: satu menyentuh batin masyarakat, yang lain membentuk kerangka sosialnya.
Perbedaan bukan kelemahan. Dalam kasus NU dan Muhammadiyah, perbedaan itu justru menjadi kekuatan. Dalam satu desa bisa ada masjid Muhammadiyah dan langgar NU berdiri berdampingan. Satu azan dengan irama padang pasir, satu dengan tembang Jawa. Tetapi keduanya menghadap kiblat yang sama. Membaca kitab yang sama. Mengucap salam yang sama.
Di situlah pelajaran terbesar kita: bahwa Islam Indonesia tidak pernah lahir dari satu warna. Ia lahir dari percampuran, dari kompromi, dari kesediaan untuk berbeda tanpa saling menyingkirkan.
Dan setiap kali dua jam yang berbeda itu berdetak, ketika satu memulai puasa dan yang lain belum, kita diingatkan kembali: barangkali bukan soal siapa yang lebih tepat, tetapi siapa yang lebih bisa menerima bahwa kebenaran itu tak selalu tunggal, dan bahwa cahaya bisa datang dari dua arah.
Dan barangkali juga, seperti kata seorang penyair yang saya lupa namanya, “kita tak perlu menjadi satu untuk berjalan bersama.” Sebab yang satu, dan yang lainnya, sama-sama membawa lentera. Dan lentera-lentera itu tak harus seragam untuk menerangi jalan yang gelap.
Editor:
Agung S Bakti
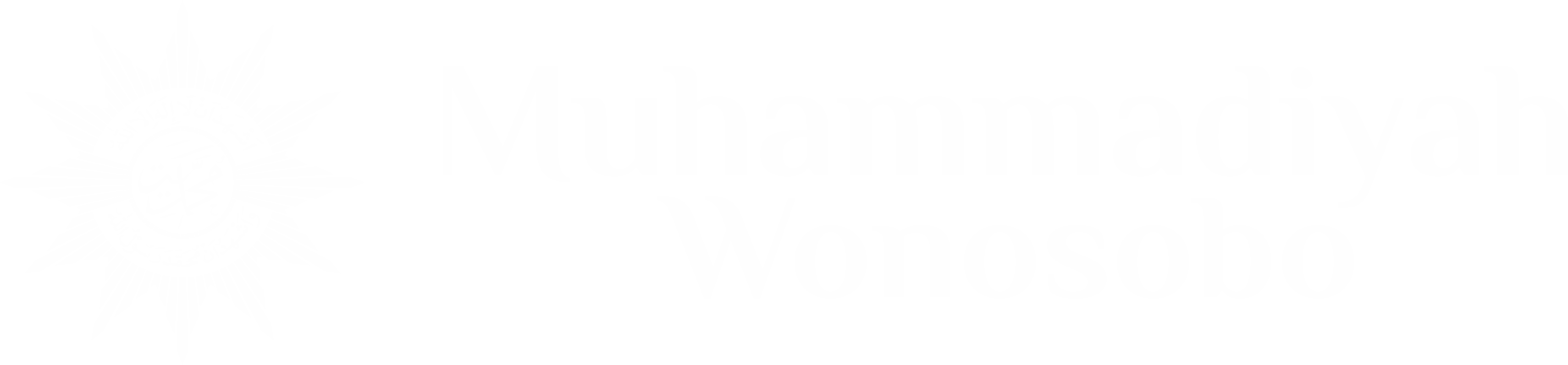




Comments
No comments yet. Be the first to comment!