
Oleh Fahmi Salim, Ketua Umum Fordamai/Ketua Bidang Tabligh Global MT PP Muhammadiyah
Setiap pertengahan bulan Sya‘ban, umat Islam di Indonesia kembali menyaksikan perdebatan yang berulang: apakah malam Nisfu Sya‘ban memiliki keutamaan, apakah boleh dihidupkan dengan ibadah berjamaah, dan apakah tradisi seperti membaca Yasin dan doa bersama tergolong bid‘ah.
Ironisnya, polemik ini kerap lebih menonjol daripada substansi spiritual yang seharusnya menjadi ruh ibadah itu sendiri.
Padahal, dalam sejarah Islam, Nisfu Sya‘ban adalah contoh klasik perbedaan ijtihadiyah yang sejak awal diakui keberadaannya oleh para ulama, tanpa melahirkan permusuhan.
Jejak Sejarah Ulama Syam
Yang sering luput dari perdebatan populer adalah fakta historis bahwa pengagungan malam Nisfu Sya‘ban pertama kali dikenal luas di wilayah Syam (Syiria–Palestina), bukan hasil rekayasa ulama belakangan. Fakta ini direkam secara jelas oleh Ibnu Rajab al-Hanbali dalam karya monumentalnya Laṭā’if al-Ma‘ārif.1 (Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Laṭā’if al-Ma‘ārif fīmā li Mawāsim al-‘Ām min al-Waẓā’if, Beirut: Dār Ibn Kathīr, hlm. 261–266.)
Sejumlah tabi‘in besar Syam seperti Khalid bin Ma‘dan, Makhul ad-Dimashqi, dan Luqman bin ‘Amir tercatat menghidupkan malam Nisfu Sya‘ban dengan ibadah, bahkan secara berjamaah di masjid.2 (Ibid.) Tradisi ini tumbuh dari pemahaman terhadap hadis-hadis tentang keutamaan malam tersebut, terutama hadis yang menyatakan bahwa Allah menampakkan rahmat dan ampunan-Nya pada malam Nisfu Sya‘ban kecuali bagi orang musyrik dan orang yang bermusuhan.3 (Ibn Ḥibbān, Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, no. hadis 5665)
Meskipun sebagian sanad hadis-hadis ini dinilai lemah, banyak ulama menerima keutamaannya dalam kerangka fadhā’il al-a‘māl. Pendekatan ini ditegaskan oleh kaidah yang dijelaskan Imam an-Nawawi bahwa hadis dha‘if dapat diamalkan dalam keutamaan amal selama tidak palsu dan tidak diyakini sebagai kewajiban atau sunnah yang mengikat.4 (an-Nawawī, al-Majmū‘ Sharḥ al-Muhadhdhab, Beirut: Dār al-Fikr, jil. 3, hlm. 125–126.)
Bahkan, Imam Isḥāq bin Rāhūyah, seorang imam besar hadis dan guru Imam al-Bukhari, secara tegas menyatakan bahwa shalat berjamaah di masjid pada malam Nisfu Sya‘ban bukan bid‘ah.5 (Ibn Rajab al-Ḥanbalī, Laṭā’if al-Ma‘ārif, hlm. 264. ) Ini menunjukkan bahwa praktik tersebut memiliki akar dalam tradisi salaf, meskipun tidak bersifat universal.
Ikhtilaf yang Dewasa, Bukan Polarisasi
Namun, penting dicatat bahwa tidak pernah ada ijma‘ tentang bentuk ibadah khusus di malam Nisfu Sya‘ban. Imam besar penduduk Madinah seperti Imam Malik tidak mengamalkannya dan menolak pengkhususan ibadah tertentu,6 (lihat: Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istidhkār, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, jil. 2, hlm. 62. ) sementara Imam al-Awza‘i, imam fiqh negeri Syam, mengakui keutamaan malamnya tetapi tidak menyukai praktik berjamaah yang dibakukan.
Ibnu Taimiyah menegaskan posisi moderat dalam persoalan ini: keutamaan malam Nisfu Sya‘ban memiliki dasar, tetapi tidak ada dalil sahih yang mewajibkan atau membakukan bentuk ibadah tertentu.7 (lihat: Ibn Taymiyyah, Majmū‘ al-Fatāwā, Riyadh: Majma‘ al-Malik Fahd, jil. 23, hlm. 131–133. ) Karena itu, ia menolak sikap saling mengingkari dalam masalah ijtihadi semacam ini.8 (Ibid.)
Yang menarik, perbedaan ini tidak pernah berubah menjadi konflik identitas. Imam Malik tidak membid‘ahkan ulama Syam. Ulama Syam tidak menganggap Madinah “kurang sunnah”. Ikhtilaf tetap berada dalam koridor adab dan ilmu.
Bandingkan dengan kondisi hari ini. Nisfu Sya‘ban tidak lagi dipahami sebagai perbedaan ijtihadiyah, tetapi dipakai sebagai alat klasifikasi sosial: siapa tradisionalis, siapa puritan, siapa dianggap lurus, siapa dianggap sesat. Inilah titik di mana masalah sebenarnya muncul—bukan pada amalan, tetapi pada cara beragama.
Praktik Nisfu Sya’ban di Indonesia
Pada akhirnya, polemik seputar Nisfu Sya‘ban di Indonesia tidak boleh berhenti pada romantisasi tradisi atau sekadar seruan toleransi yang hampa dari kejujuran ilmiah. Ketika praktik ibadah mahdhah—seperti shalat khusus dengan bilangan tertentu, doa-doa dengan niat panjang umur dan kelapangan rezeki, serta keyakinan bahwa malam Nisfu Sya‘ban adalah saat penetapan seluruh takdir dan ajal manusia—secara tegas ditolak oleh otoritas ulama sebesar Imam an-Nawawi dan Syaikh ‘Athiyyah Shaqr, maka persoalan ini bukan lagi khilafiyah ringan, melainkan ujian serius bagi integritas keilmuan umat. Mengabaikan koreksi tersebut berarti membiarkan tradisi menggeser dalil, dan sentimen kolektif mengalahkan metodologi ilmiah yang selama berabad-abad menjadi penyangga Ahlus Sunnah.
Namun pada saat yang sama, koreksi ilmiah yang sahih tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap umat awam, sebab kesalahan mereka lahir dari pewarisan tradisi, bukan dari kesengajaan menyalahi agama. Di titik inilah adab beragama menemukan maknanya: berani mengatakan yang benar dengan dalil yang jujur, sekaligus menjaga hikmah dakwah agar kebenaran tidak berubah menjadi alat polarisasi. Tanpa keseimbangan ini, umat tidak hanya kehilangan ketepatan beragama, tetapi juga kehilangan kebijaksanaan dalam merawat persatuan.
Defisit Adab di Tengah Banjir Dalil
Umat Islam modern tidak kekurangan dalil, tetapi sering kekurangan adab. Media sosial mempercepat polarisasi: potongan ceramah menggantikan kajian utuh, emosi mengalahkan metodologi, dan klaim kebenaran menggeser kerendahan hati ilmiah.
Ironisnya, hadis tentang Nisfu Sya‘ban justru menegaskan bahwa permusuhan adalah penghalang ampunan. Ketika malam yang dikaitkan dengan rahmat malah melahirkan saling mencela, maka yang gagal bukan tradisi atau pemurnian agama, melainkan pemahaman terhadap maqāṣid ibadah itu sendiri.
Belajar dari Ulama, Bukan dari Polarisasi
Ulama klasik telah memberi teladan yang jelas bahwa: a) Keutamaan waktu tidak selalu berarti ada ritual baku, b) Amalan ijtihadi tidak boleh dipaksakan, c) Perbedaan tidak identik dengan penyimpangan
Kaedah “lā inkāra fī masā’il al-khilāf” (tidak ada pengingkaran dalam masalah yang diperselisihkan) bukan slogan kompromistis, melainkan fondasi peradaban ilmu Islam. Tanpanya, setiap perbedaan kecil akan berubah menjadi konflik besar.
Mengembalikan Ruh Nisfu Sya‘ban
Nisfu Sya‘ban seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan arena konfrontasi. Sejarah ulama Syam mengajarkan bahwa menghidupkan malam tersebut adalah pilihan ibadah yang sah secara ijtihadi, bukan kewajiban yang mengikat. Sejarah ulama Madinah mengingatkan bahwa meninggalkannya juga pilihan yang sah, tanpa cela.
Dalam konteks umat yang mudah terbelah, mungkin yang paling mendesak hari ini bukan memperdebatkan siapa paling benar, tetapi belajar kembali adab berbeda. Sebab agama ini tidak hanya dibangun dengan dalil dan sanad, tetapi juga dengan akhlak dan kelapangan dada.
Jika malam ampunan dosa justru melahirkan permusuhan, maka yang perlu diperbaiki bukan amalan orang lain, melainkan cara kita memandang sesama Muslim.
Wallahu a’lam.
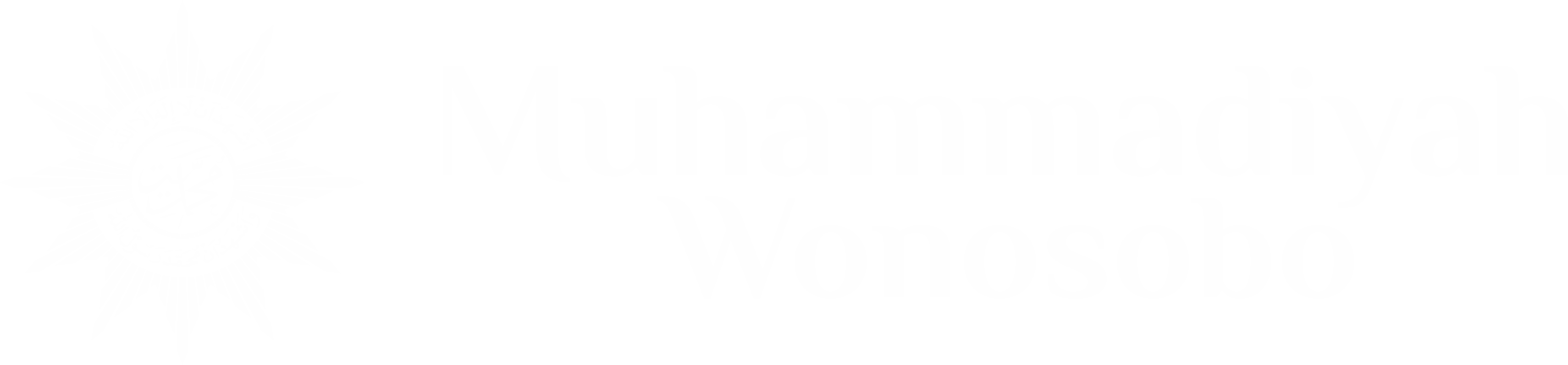




Comments
No comments yet. Be the first to comment!