
Oleh : Rudyspramz, MPI
Hijrah dalam sejarah Islam adalah peristiwa peradaban. Rasulullah SAW berpindah dari Mekah ke Madinah bukan sekadar berpindah tempat, melainkan berpindah strategi, membangun tatanan sosial, politik, dan spiritual yang memungkinkan nilai-nilai Islam tumbuh secara utuh. Mekah saat itu terlalu sempit oleh tekanan, Madinah memberi ruang bagi peradaban.
Dalam konteks modern, hijrah mengalami pergeseran makna. Ia tidak lagi semata historis, melainkan personal dan eksistensial. Hijrah menjadi kesadaran diri—seringkali berawal dari luka, kegersangan hidup, kelelahan batin, dan pencarian makna. Dari ingkar menuju taat, dari maksiat menuju kemuliaan. Dan itu sah, bahkan mulia.
Al-Qur’an sendiri adalah as-syifa’, obat bagi hati yang terluka, pikiran yang lalai, dan jiwa yang lelah. Maka ketika seseorang menemukan ketenangan melalui hijrah, mengalami kedamaian dengan kembali mengingat Allah, tidak ada yang keliru di sana. Hijrah adalah proses penyembuhan.
Namun, di sinilah refleksi perlu dimulai.
Dalam pendekatan Tarjih, kita mengenal wilayah irfani—ranah hati, intuisi, kalbu—yang dekat dengan dunia tasawuf dan tarekat dalam tradisi klasik Islam. Muhammadiyah sendiri lebih menekankan bayani dan burhani: teks yang dipahami secara rasional, dan akal yang diuji secara ilmiah, menuju puncak ihsan dan diwujudkan dalam akhlak dan amal shalih. Iman, Ilmu dan Amal adalah tradisi Muhammadiyah membekali kadernya tidak hanya kuat secara spiritual tapi juga aksional dan tranformatif, menjadikan kadernya menjadi elite agama dan sosial yang mencerahkan umat dan bangsa
Fenomena hijrah hari ini banyak bertumpu pada irfani : kuat di rasa, tetapi sering lemah di refleksi kritis.
Hijrah lalu menciptakan “dunia baru”: lebih taat, lebih religius secara simbolik, namun cenderung eksklusif. Penampilan menjadi identitas utama; pakaian lebar, warna gelap, batas sosial yang kian tegas. Ketika simbol menjadi pusat, diskusi pemikiran sering dianggap mengganggu iman.
Fenomena ini makin kuat ketika hijrah dikapitalisasi oleh figur publik. Publik figur yang berhijrah menjadi magnet, terutama bagi kaum perempuan. Mereka hadir sebagai teladan, sebagai cermin harapan bahwa hidup bisa berubah menjadi lebih baik. Di sinilah emosi bekerja.
Tak mengherankan jika pengajian selalu dipenuhi kaum hawa. Perempuan memikul beban lahir dan batin yang besar sebagai istri, ibu dan sebagai perempuan, mulai dari mendidik anak, melayani suami, mengatur keuangan keluarga apalagi kalau dia juga bekerja. Allah memang menciptakan perempuan dengan dominasi rasa, dan rasa yang lelah butuh ruang pelepasan. Pengajian menjadi oase: tempat menangis, berharap, dan merasa dipahami.
Kemudian muncullah dai-dai muda : tampan, lembut, jenaka, hadir di komunitas perempuan kelas menengah ke atas. Ketika hati sudah tersentuh, loyalitas pun tumbuh. Mobilisasi apa pun—termasuk dana—menjadi mudah, apalagi jika dibungkus dengan narasi kebaikan.
Namun pertanyaan pentingnya: bagaimana dengan pemikiran? Bagaimana dengan kritisisme? Bagaimana dengan kedewasaan intelektual umat ?
Isu seperti cadar, warna pakaian, model busana yang serba tertutup sering dianggap “hak pribadi” yang tak boleh disentuh diskusi, termasuk soal peran publik perempuan, relasi suami istri, poligami berhadapan dengan isu-isu global tentang kesetaraan, hak asasi, kemanusiaan, demokrasi dll. Bicara Diskursus Perempuan Islam dalam modernitas selalu menarik dan mengundang perdebatan dan ini layak dikaji oleh Muhammadiyah yang mengklaim diri sebagai gerakan tajdid.
Teks seringnya dibaca secara literal, padahal ini wilayah muamalah duniawiyah konteks disisihkan. Peradaban Islam di bangun dengan wacana, diskusi dan ilmu pengetahuan dan kalau sekedar mempertanyakan, iman tidak runtuh hanya karena dialog.
Hijrah yang berhenti di simbol berisiko mandek. Hijrah yang menolak nalar bisa kehilangan arah. Padahal Islam adalah agama hati dan akal, rasa dan pikir.
Mungkin tugas kita hari ini bukan menghakimi fenomena hijrah, melainkan menemani ia bertumbuh. Dari hijrah emosional menuju hijrah intelektual. Dari kesalehan personal menuju kesalehan sosial. Dari rasa yang hangat menuju akal yang tercerahkan.
Sebab hijrah sejati bukan hanya soal bagaimana kita berpakaian, tetapi bagaimana kita bersikap. Bukan hanya tentang seberapa jauh kita menjaga diri, tetapi seberapa luas kita membuka hati dan pikiran.
Hijrah adalah jalan pulang. Dan jalan pulang peradaban Islam yang matang selalu melewati hati dan nalar.
wallahu a'lam
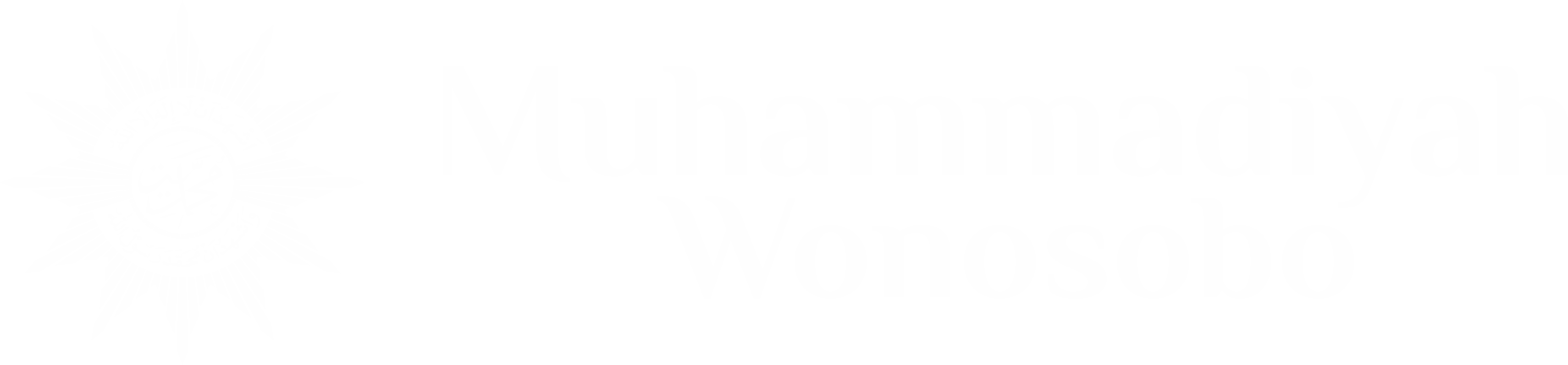




Comments
No comments yet. Be the first to comment!