
Gunoto Saparie, Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah
Sejarah kadang terlalu tergesa. Ia menyukai letupan, tanggal, dan peristiwa: 17 Agustus, teks proklamasi, sebuah pidato, sebuah siaran radio. Seakan-akan kemerdekaan adalah sebuah ledakan yang meletus begitu saja di satu siang, pukul 10.00 WIB.
Tetapi, barangkali sejarah yang lebih jujur adalah yang berjalan diam-diam, di gang-gang kota, di ruang kelas kecil, di mimbar musala, di tangan para guru yang tak dikenal, dan di balik nama yang hampir tak disebut: Muhammadiyah.
Ketika Kiai Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada 1912, ia tidak membawa bendera. Ia tidak datang dengan janji revolusi atau hasrat mengangkat senjata. Ia malah membuka sekolah, mendirikan klinik, mencetak buku, dan mengajarkan anak-anak membaca dan menulis. Ia meyakini bahwa merdeka tidak bisa dimulai dengan senjata jika kepala masih kosong dan dada masih hampa.
Ahmad Dahlan hidup dalam masa ketika dunia seperti kiamat kecil. Gunung Krakatau meletus, tanah pecah, dan udara gelap berhari-hari. Sementara itu, di bumi yang tak sempat istirahat, kolonialisme mencengkeram. Peperangan meletus di Aceh, di Jawa, di Bali, di Ambon. Tubuh Nusantara luka. Jiwa bangsanya lebih luka lagi karena mereka tak tahu apa yang sedang diperjuangkan, bahkan belum tahu siapa mereka.
Maka, seperti Imam Al-Ghazali di abad ke-11 yang memilih menulis Ihya’ Ulumuddin di tengah ancaman Salibis dan kehancuran spiritual kaum Muslim, Ahmad Dahlan pun memilih mendirikan madrasah. Bukan karena ia takut perang, tetapi karena ia tahu: yang pertama harus dikalahkan adalah kebodohan.
Muhammadiyah bukan organisasi revolusioner seperti Sarekat Islam yang bermassa besar, bukan Budi Utomo yang elitis, atau Partai Komunis yang militan. Tetapi, justru karena itu, ia bertahan dan perlahan membentuk dasar bangsa. Ia tak tergoda oleh euforia perlawanan yang berumur pendek. Ia membangun dari bawah, dari akal, dari hati, pun dari perut.
Konsep yang dibawa Muhammadiyah jauh melampaui zamannya. Pendidikan untuk perempuan, misalnya, dianggap ganjil bahkan oleh kalangan pesantren. Tetapi, Ahmad Dahlan mengajar Siti Walidah, istrinya, untuk menjadi pemimpin. Ia melahirkan Aisyiyah, mendidik anak-anak yatim, dan membangun rumah sakit. Ia menulis tafsir Al-Ma’un bukan di atas podium, tetapi di dapur, di jalan, di klinik, dan di ruang kelas.
Yang ia bangun kemudian hari disebut pembangunan manusia (human development), atau dalam istilah kontemporer: SDG’s—Sustainable Development Goals. Ahmad Dahlan tak mengenal istilah itu, tetapi ia hidup di dalamnya. Ia memperbaiki gizi, memperluas wawasan, mencetak guru, melatih karakter, dan membentuk pemimpin. Semua dilakukan dalam kesunyian yang konsisten.
Maka, ketika kemerdekaan akhirnya datang, seperti bunga yang mekar setelah musim panjang, ia bukan hasil dari satu hari. Ia hasil dari perjalanan panjang. Muhammadiyah ada di belakangnya: dalam darah para pejuang, dalam pikiran para pemimpin, dalam nilai yang membentuk bangsa.
Benar, Muhammadiyah adalah organisasi yang paling banyak menyumbang Pahlawan Nasional. Tetapi, ukuran itu mengecilkan karena tak semua pahlawan dikenal dan tak semua perjuangan tercatat. Ada guru di pelosok yang menyalakan semangat kebangsaan tanpa pernah masuk buku sejarah. Ada bidan Muhammadiyah yang menyelamatkan ratusan nyawa bayi di masa darurat perang. Ada pemuda Hizbul Wathan yang gugur tanpa nama. Ada kepala sekolah yang menjual sepeda demi membayar buku muridnya. Mereka tidak diberi bintang jasa, tetapi mereka meletakkan batu pertama.
Hari ini, kita menyebut Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern. Namun, mungkin itu tak cukup. Ia adalah organisasi kehendak merdeka. Ia tidak menggantungkan nasib bangsa pada kekuatan asing atau pada karisma seorang tokoh. Ia menyiapkan bangsa ini untuk merdeka, jauh sebelum merdeka diproklamasikan. Ia menyembuhkan luka batin rakyat yang patah harapan dan merawat cahaya di dalam gelap.
Kemerdekaan bukan hanya tanggal, bukan hanya teks. Ia adalah keadaan jiwa. Dan Muhammadiyah, dengan segala kesederhanaannya, telah membuktikan bahwa bangsa ini bisa merdeka karena pernah diajarkan untuk percaya pada dirinya sendiri. Mungkin, justru di situlah letak kemuliaannya.
Barangkali sejarah selalu memilih jalan yang senyap, seperti Muhammadiyah. Ia tidak datang dengan genderang perang, tak pula dengan poster revolusi. Ia hadir lewat suara azan di musala kampung, lewat papan tulis di kelas-kelas sore, lewat lembar-lembar dakwah yang dicetak dengan tinta sabar. Tetapi, justru dari kesenyapan itu, kemerdekaan lahir dengan denyut yang lebih dalam: bukan hanya merebut tanah, melainkan mengisi jiwa.
Muhammadiyah memang tidak mendirikan republik ini, tetapi barangkali republik ini berdiri juga karena Muhammadiyah. Ia tidak pernah mengklaim kemerdekaan sebagai hasil perjuangannya, tetapi darah dan keringatnya ada di antara lorong-lorong waktu menuju 17 Agustus. Di masa ketika bangsa ini masih mencari nama untuk dirinya sendiri, Muhammadiyah sudah lebih dulu merajut identitas melalui pendidikan, kesehatan, dan tentu saja: iman.nya
Ada Ki Bagus Hadikusumo, sosok bersorban yang kelak menandatangani Piagam Jakarta dengan sejumput kegelisahan. Ia tak hanya hadir sebagai Ketua Majelis Tabligh. Ia menulis sejarah dalam sunyi: sebagai pemikir, pendebat, dan saksi pada lahirnya dasar negara. Ia tak menolak Pancasila, tetapi menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tak pernah bertentangan dengan kebangsaan jika Islam kita pahami sebagai cahaya, bukan tembok.
Ada pula K.H. Mas Mansyur, ulama dari Surabaya, yang lebih sering tampak seperti aktivis daripada ustaz. Ia bergabung dalam BPUPKI, duduk bersama Soekarno dan Hatta, menjadi bagian dari Empat Serangkai yang di kemudian hari disebut “kolaborator” oleh sejarah yang tak sabar. Tetapi, justru di tengah zaman yang gelap itulah, Mas Mansyur menyalakan obor nasionalisme religius—bukan nasionalisme sempit, bukan pula Islam yang eksklusif. Ia percaya, negeri ini bisa dibangun dengan iman dan ilmu sekaligus.
Kemudian, ada Adam Malik, yang lebih dikenal sebagai diplomat daripada dai. Tetapi, ia belajar dari Muhammadiyah bahwa kata-kata bisa menjadi peluru. Di hari proklamasi, ia bukan hanya menyaksikan sejarah, melainkan menyebarkannya. Ia mewartakan kemerdekaan dengan mesin tik dan kabel berita, meyakinkan dunia bahwa bangsa ini bukan bayang-bayang Jepang, tetapi suara yang lahir dari rahim penderitaan panjang.
Dan Soekarno. Ia bukan “tokoh Muhammadiyah”, tetapi ia anak dari keluarga yang bersentuhan erat dengan Muhammadiyah. Ia mengaji, katanya, pada Kiai Ahmad Dahlan, atau setidaknya merasakan bagaimana organisasi itu membentuk cara berpikir tentang keislaman yang modern dan membumi. Tak heran jika dalam pidatonya, Soekarno sering menyebut nama-nama dari organisasi itu sebagai wujud penghormatan dan utang intelektual.
Peran Muhammadiyah bukan sekadar di mimbar masjid, tetapi juga di medan pertempuran. Laskar-laskar Hizbul Wathan, yang awalnya dididik untuk baris-berbaris dan mencintai tanah air, tiba-tiba harus memanggul senapan. Mereka bukan tentara, tetapi berjuang dengan iman yang sederhana: bahwa penjajahan adalah dosa.
Ada pula cerita tentang Kiai Abdul Mukti, yang konon ikut menyarankan tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan, tanggal ganjil yang dipilih bukan karena strategis militer, melainkan karena bertepatan dengan Jumat Legi, hari yang diyakini membawa berkah. Ada pula Syarif Abdul Hamid Alkadrie, Sultan Pontianak yang mendesain lambang negara Garuda, tak hanya sebagai simbol kekuasaan, tetapi sebagai perwujudan kearifan Nusantara.
Semua itu, seperti halnya Muhammadiyah sendiri, bukan pameran kehebatan. Tak ada parade. Tak ada deklarasi. Hanya kerja yang diam-diam.
Hari-hari ini, pada bulan Agustus, ketika kita memperingati kemerdekaan, kita menyanyikan “Indonesia Raya” dengan suara penuh. Tetapi, mungkin kita lupa bahwa sebagian dari kemerdekaan itu disumbangkan oleh mereka yang tidak bersorak, tetapi berdoa. Oleh mereka yang tidak memegang senjata, tetapi membuka sekolah. Oleh mereka yang tidak duduk di kursi parlemen, tetapi berdiri di depan kelas atau di atas mimbar.
Dan mungkin itulah cara Muhammadiyah bekerja: seperti hujan malam hari. Tak terlihat, tetapi menyuburkan.
Editor:
Agung S Bakti
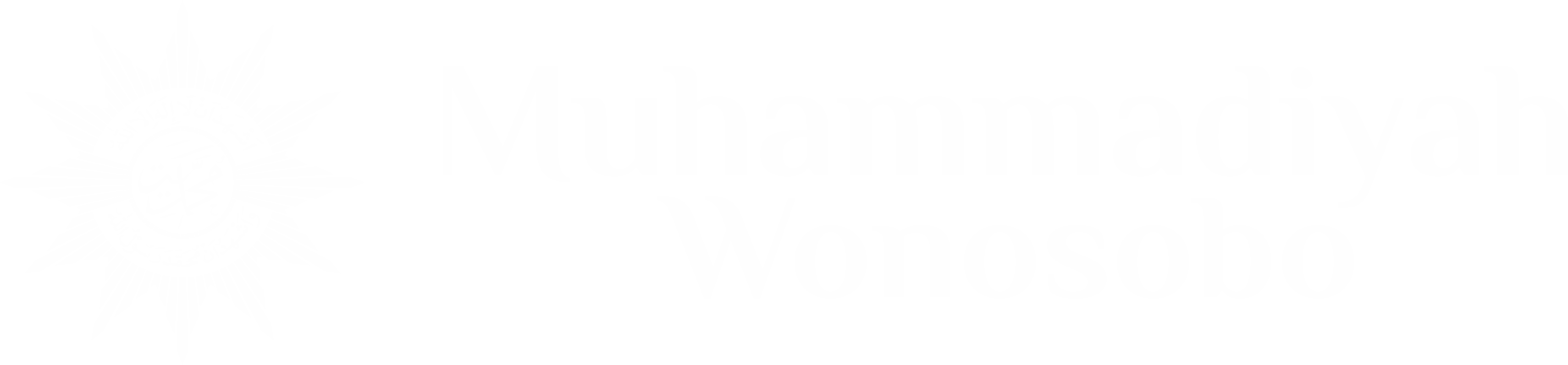




Comments
No comments yet. Be the first to comment!