
oleh : Rudyspramz, MPI
Perbedaan penentuan awal bulan qamariyah, khususnya awal Ramadhan dan 1 Syawal, telah menjadi fenomena berulang dalam kehidupan umat Islam Indonesia. Perbedaan ini bukan sekadar persoalan teknis astronomi, melainkan berkelindan dengan dimensi teologis, metodologis, dan sosial-keagamaan yang kompleks.
Sejak awal 1990-an, perbedaan semakin mengemuka akibat perbedaan dalam memahami hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim “Shumu li ru’yatihi…” (berpuasalah karena melihat hilal). Sebagian memahami “rukyat” secara literal sebagai pengamatan langsung hilal, sebagaimana dipraktikkan oleh Nahdlatul Ulama dan pemerintah melalui mekanisme rukyat. Sementara itu, Muhammadiyah memaknai hadis tersebut sebagai isyarat penggunaan ilmu pengetahuan (hisab) dalam menentukan awal bulan.
Pemerintah Indonesia berupaya menjembatani perbedaan tersebut melalui konsep imkanur rukyat—perpaduan hisab dan rukyat—yang kemudian diselaraskan dengan kriteria regional MABIMS (Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura). Kriteria ini menetapkan batas minimal visibilitas hilal (misalnya tinggi 3 derajat dan elongasi tertentu). Namun di sisi lain, metode Muhammadiyah berkembang menggunakan hisab wujudul hilal dan kini mengembangkan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang berorientasi global.
Menurut astronom BRIN, Thomas Jamaluddin, perbedaan akan terus terjadi selama metode yang digunakan berbeda secara prinsip. KHGT berpotensi memperluas perbedaan karena menggunakan konsep hilal global, sedangkan imkanur rukyat berbasis visibilitas lokal-regional.
Dalam perspektif astronomi, masing-masing metode memiliki dasar ilmiah dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, meski menghasilkan kesimpulan berbeda, sepanjang dalam ranah pengembangan ilmu pengetahuan.
Namun dari sisi teologis dan sosiologis persoalan menjadi lebih sensitif ketika perbedaan terjadi pada 1 Syawal. Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa perbedaan pada hari raya dapat melampaui ranah furu’iyah (cabang) dan menyentuh wilayah ushuliyah (prinsip), karena terdapat konsekuensi hukum: haram berpuasa pada 1 Syawal, artinya ada yang salah dalam penetapan 1 Syawal. Dalam situasi ini, secara logika normatif, seolah ada dua penetapan hukum yang saling berlawanan dalam satu ruang umat
Namun demikian, perbedaan ini sejatinya lebih mencerminkan keragaman metodologi ijtihad dalam Islam daripada pertentangan akidah. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa perbedaan dalam penentuan awal bulan telah terjadi sejak masa klasik, terutama di wilayah yang berjauhan secara geografis. Perbedaan tersebut dikelola dalam kerangka toleransi ilmiah dan pengakuan terhadap otoritas masing-masing komunitas.
Posisi pemerintah sebagai pelindung dan pemersatu umat menjadi krusial. Menyatukan secara administratif belum tentu menyatukan secara epistemologis. Memaksakan keseragaman dapat memunculkan resistensi, sementara membiarkan fragmentasi tanpa dialog juga berpotensi menimbulkan kebingungan umat. Jalan tengahnya adalah memperkuat literasi keagamaan dan astronomi, membuka ruang musyawarah ilmiah, serta menumbuhkan kesadaran bahwa perbedaan metode bukanlah ancaman bagi persatuan, melainkan bagian dari dinamika ijtihad.
Dengan demikian, perbedaan awal Ramadhan dan Syawal hendaknya dipandang sebagai ruang refleksi bersama untuk memperdalam integrasi antara ilmu falak, fikih, dan kebijakan publik. Persatuan umat tidak selalu identik dengan keseragaman tanggal, tetapi dengan kedewasaan dalam menyikapi perbedaan secara ilmiah, proporsional, dan berkeadaban.
wallahu a'lam
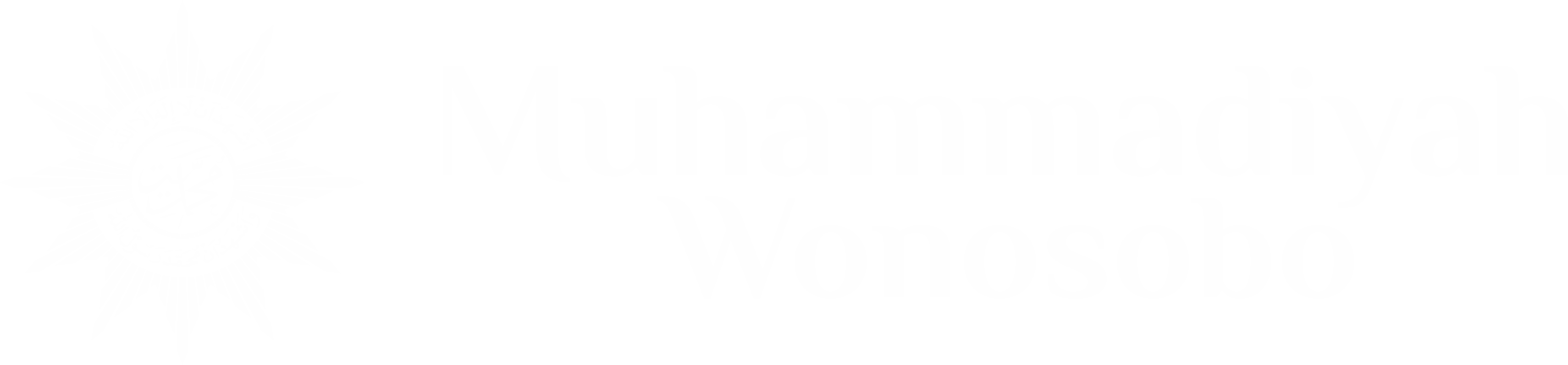




Comments
No comments yet. Be the first to comment!